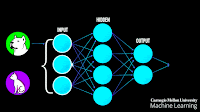Thursday, September 25, 2025
Memahami Buzzer sebagai 'Tentara' Digital Bayaran
Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit
Fenomena buzzer di Indonesia bukan sekadar “akun berisik” di media sosial, tetapi merupakan mesin propaganda modern yang berperan besar dalam membentuk opini publik. Buzzer bekerja secara sistematis, terstruktur, dan terorganisir, sehingga dampaknya terhadap demokrasi sangat signifikan.
Dari Promosi Produk ke Senjata Politik
Awalnya, buzzer muncul sekitar tahun 2009 hanya untuk kepentingan promosi produk dan tren komersial. Namun sejak Pilkada DKI 2012, peran buzzer mulai dipolitisasi. Mereka tidak lagi sekadar memasarkan, melainkan menjadi alat untuk menyerang lawan politik, membentuk citra, hingga memanipulasi opini publik
Propaganda Murah tapi Efektif
Bagi penguasa, buzzer adalah alat propaganda murah namun berdampak besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat anggaran pemerintah untuk aktivitas digital (influencer dan buzzer) mencapai Rp1,29 triliun (2014–2020)
Buzzer digunakan untuk membungkam kritik, menyebarkan disinformasi, hingga menciptakan ilusi dukungan publik.
Dampak Serius bagi Demokrasi
Kehadiran buzzer mengakibatkan beberapa kerusakan utama:
Distorsi Kebenaran – isu penting ditenggelamkan oleh kebisingan propaganda
Normalisasi Kekerasan Digital – seperti doxing, intimidasi, hingga kriminalisasi kritik
Erosi Kepercayaan Publik – masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan manipulasi
Pembiasan Kolektif – kebohongan dianggap lumrah karena terus diulang
Bagaimana Melawannya?
Buzzer adalah wajah baru politik kotor yang kini hadir terang-terangan di ruang digital. Namun masyarakat sipil masih punya senjata: kesadaran kritis, solidaritas digital, dan keberanian moral
Dengan mendukung jurnalisme independen dan menolak ikut menyebarkan kebohongan, publik dapat menjaga ruang demokrasi dari manipulasi buzzer.
Simak Video Lengkapnya
Kuasa, Politik dan Machiavelli
Oleh: M. Yunasri Ridhoh (Pengurus Pemuda ICMI Makassar/Dosen FEB UNM)
Suatu sore di sebuah kedai kopi kampus, seorang mahasiswa yang juga pengurus organisasi mahasiswa menunjukkan buku lusuh kepada temannya. Sampulnya hitam, judulnya Il Principe. “Katanya ini buku yang membuat banyak penguasa menjadi bengis,” ujarnya sambil tersenyum nakal.
Temannya menatap curiga, “Jangan-jangan kamu setuju dengan sistem diktator?” Mereka tertawa. Di meja sebelah, saya menyimak perbincangan itu. Saya jadi tertarik menuliskannya. Tidak kah terbersih tanya di benak kita, mengapa sebuah buku yang ditulis lebih dari lima abad lalu masih bisa memicu debat sengit di meja kopi, paling tidak dibaca oleh mahasiswa abad ke-21?
Di situlah nama Niccolò Machiavelli terus hidup, terus relevan. Ia tidak hanya hadir dalam ruang kuliah filsafat politik, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Hampir setiap kali kita membicarakan pemimpin yang lihai sekaligus licik, nama Machiavelli muncul sebagai rujukan.
Dari Florence ke Pengasingan
Niccolò Machiavelli, siapa yang tak mengenalnya? Nama itu kerap berseliweran dalam setiap diskusi politik, umumnya selalu dikaitkan dengan adagium “tujuan menghalalkan segala cara”. Stigma itu melekat begitu kuat, sampai-sampai istilah Machiavelian identik dengan tipu daya, kelicikan, dan kekuasaan yang busuk.
Padahal, jika kita mau sedikit bersabar menelusuri teks-teksnya, Machiavelli tidaklah sesederhana itu. Ia bukan sekadar penganjur intrik, melainkan salah satu pemikir politik paling berpengaruh dalam membentuk wajah modernitas.
Machiavelli lahir di Florence, 3 Mei 1469, dari keluarga terdidik dan cukup berada. Sejak muda ia akrab dengan dunia pemerintahan. Posisinya sebagai pejabat republik memberinya akses luas ke diplomasi dan urusan militer. Ia bergaul dengan bangsawan, menyaksikan intrik, sekaligus mencatat gejolak zamannya.
Namun keberuntungan itu terhenti ketika keluarga Medici kembali berkuasa. Machiavelli ditangkap, disiksa, lalu dipenjara. Setelah dibebaskan, ia menyingkir ke sebuah villa tua di pinggiran kota.
Justru dalam pengasingan itu lahir karya yang membuat namanya abadi: Il Principe (Sang Pangeran), rampung sekitar 1513 meski baru terbit 1532, serta Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531). Jika Il Principe dianggap sebagai buku panduan merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka Discorsi adalah renungan lebih panjang tentang republik, hukum, dan pentingnya moral dalam politik.
Keduanya bagai dua sisi koin yang sama, satu bicara cara meraih kekuasaan, yang lain bicara cara menjaga republik agar tak hancur.
Antara Virtù dan Fortuna
Kekuatan Machiavelli ada pada keberaniannya menanggalkan moralitas tradisional dari perbincangan politik. Ia menulis politik sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut agama atau filsafat klasik. Di sinilah ia sering disalahpahami.
Bagi Machiavelli, seorang penguasa tidak bisa selalu baik hati. Kadang ia perlu culas, licik, bahkan kejam, jika keadaan menuntut. “Lebih aman bagi seorang pangeran untuk ditakuti daripada dicintai,” tulisnya dalam Il Principe. Terdengar kejam sekali, tapi itu sangat realistis.
Tetapi ia tidak sedang mengajak manusia menjadi iblis. Machiavelli hanya menunjukkan realitas bahwa kekuasaan adalah medan yang keras. Untuk bertahan, seorang penguasa membutuhkan virtù. Kata ini kerap diterjemahkan sebagai “keutamaan”, tetapi dalam pemahaman Machiavelli, virtù lebih dekat ke keberanian, ketegasan, kelincahan, bahkan kelihaian. Virtù adalah kapasitas seorang pemimpin untuk menghadapi situasi tak menentu.
Lawan virtù adalah fortuna—nasib, keberuntungan, atau situasi tak terduga. Machiavelli menulis, “Fortuna ibarat sungai yang dahsyat, yang ketika meluap menghancurkan segalanya. Namun manusia bisa membendungnya, bisa mengarahkannya.” Dengan virtù, penguasa dapat menjinakkan fortuna, meski tak pernah sepenuhnya menguasainya.
Di sinilah realisme Machiavelli terasa begitu modern: ia menolak menyerahkan politik pada doa semata, dan justru menekankan strategi, kalkulasi, serta keberanian manusia untuk melawan nasib.
Negara, Agama, dan Rakyat
Salah satu gagasan paling provokatif Machiavelli adalah relasi antara negara dan agama. Di zamannya, Gereja Katolik memegang kendali besar atas kehidupan politik. Machiavelli menganggap itu berbahaya. Bukan berarti ia menolak agama sepenuhnya. Menurutnya, agama bisa bermanfaat sejauh ia menumbuhkan disiplin dan patriotisme. Tetapi negara tak boleh tunduk pada agama. “Agama seharusnya menjadi alat negara, bukan sebaliknya,” begitu kira-kira pesannya.
Pandangan ini tentu membuatnya dimusuhi Gereja. Pada 1559, Il Principe dimasukkan ke dalam daftar buku terlarang. Namun gagasan bahwa negara harus independen dari dominasi gereja kemudian menjadi salah satu fondasi modernitas politik Barat. Sekularisme lahir, negara berdiri di atas hukum positif, dan agama tetap hidup sebagai kekuatan moral dalam masyarakat, bukan instrumen untuk mengendalikan kekuasaan.
Menariknya, Machiavelli tidak sepenuhnya berpihak pada figur penguasa tunggal. Dalam Discorsi, ia justru menulis bahwa “orang banyak lebih bijaksana dan lebih konstan daripada seorang pangeran”. Rakyat, kata Machiavelli, cenderung memikirkan kebaikan bersama, sedangkan raja bisa saja dikuasai ambisi pribadi. “Suara rakyat adalah suara Tuhan,” tulisnya, meski tentu dalam konteks yang berbeda dengan demokrasi modern.
Di sini Machiavelli tampak ambivalen: di satu sisi ia mengagumi pangeran yang tangguh, di sisi lain ia mengakui kebijaksanaan kolektif rakyat. Ambivalensi ini wajar, sebab ia menulis dalam masa penuh ketidakpastian. Italia terpecah belah, diserbu kekuatan asing, dan ia merindukan sosok pemimpin yang kuat untuk menyatukannya. Tetapi di saat yang sama, ia sadar bahwa republik dengan hukum dan partisipasi rakyat lebih menjamin keberlanjutan negara.
Membaca Ulang Machiavelli
Mengapa Machiavelli penting untuk dibicarakan hari ini? Karena politik kita pun sering terjebak dalam dilema serupa: antara idealisme dan realitas, antara moralitas dan kebutuhan pragmatis. Kita mudah menuduh seorang pemimpin Machiavelian ketika ia bersikap keras atau licik. Tetapi lupa bahwa politik memang dunia penuh intrik, dan justru di situlah ujian kebijaksanaan muncul.
Membaca Machiavelli tidak berarti menyetujui semua gagasannya. Justru sebaliknya, membaca adalah cara untuk menguji diri: sejauh mana kita siap menghadapi kenyataan politik tanpa terjebak romantisme moral yang hampa. Machiavelli mengingatkan, negara butuh pemimpin yang berani, tetapi juga butuh sistem yang menjaga agar keberanian itu tidak berubah menjadi tirani.
Lebih jauh, Machiavelli memberi kita pelajaran tentang pentingnya berpikir kritis. Ia menulis dari pengalaman konkret, bukan dari menara gading filsafat. Ia tahu bahwa politik bukan arena malaikat, melainkan arena manusia, dengan segala kelemahan dan ambisinya. Maka, yang bisa dilakukan adalah merancang strategi terbaik agar negara tetap berdiri tegak.
Machiavelli bukanlah setan yang menjerumuskan politik ke jurang amoral. Ia adalah cermin yang memperlihatkan wajah asli kekuasaan, sekaligus menantang kita untuk lebih dewasa dalam mengelola republik. Mungkin itulah mengapa, lima abad setelah wafatnya, namanya tetap disebut, entah dengan kutukan atau dengan kekaguman.
Karena politik, seperti kata Machiavelli, selalu bergerak di antara virtù dan fortuna—antara keberanian manusia dan permainan nasib yang tak pernah bisa sepenuhnya kita kuasai atau kendalikan.