Memahami Buzzer sebagai 'Tentara' Digital Bayaran
Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit Fenomena buzzer di Indonesia bukan…
Sinergi Cendekia dan Peduli Kemanusiaan
"Kita bisa mencintai Indonesia tanpa harus mencintai pemerintahnya, apalagi pejabatnya."
Ungkapan Farid Gaban benar, ia menyadarkan kita bahwa cinta pada tanah air tidaklah sama dengan tunduk pada kekuasaan. Ia membuka satu kebenaran sederhana namun sering terlupakan: bangsa adalah entitas yang lebih besar dan lebih luhur daripada rezim yang kebetulan sedang berkuasa.
Indonesia adalah rumah bersama. Kita lahir, tumbuh, belajar, mencintai, dan bermimpi di tanah ini. Indonesia bukan sekadar nama dalam dokumen resmi atau lambang di dinding kantor-kantor pemerintah. Ia adalah cerita panjang tentang pergulatan, perjuangan dan harapan. Maka, mencintai Indonesia adalah mencintai rakyatnya yang beragam, mencintai tanah dan airnya, budayanya, bahasanya, sejarahnya yang berdarah-darah namun penuh harap, juga masa depannya yang menuntut keberanian dan pengorbanan.
Sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan, saya sering menyampaikan nilai dan pemahaman ini kepada mahasiswa, baik saat perkuliahan di ruang kelas, dalam diskusi santai di pelataran, koridor kampus, atau warung kopi. Saya mengajak mahasiswa menyadari bahwa mencintai bangsa ini tidak berarti menerima begitu saja semua keputusan pemerintah. Saya tekankan bahwa menjadi warga negara yang baik justru berarti bersikap aktif dan kritis, serta berani bertanya, bahkan menolak.
Sebaliknya, pemerintah—sebagai representasi kekuasaan yang sementara—seringkali justru menjadi penghambat idealisme itu ketika mengabdi bukan pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan golongan atau diri sendiri. Kita tidak sedang bicara tentang satu pemerintahan atau rezim tertentu, melainkan tentang prinsip yang lebih luas: pemerintah hanyalah alat, bukan tujuan.
Dalam demokrasi, bersikap kritis terhadap pemerintah bukanlah bentuk kebencian. Justru itulah bentuk kedewasaan sebagai warga negara. Kita mencintai negeri ini karena kita tak ingin melihatnya dirusak oleh kebijakan yang menyesatkan, oleh pejabat yang korup, atau oleh sistem yang tidak adil. Kritik adalah tanda cinta. Diam, justru bisa berarti abai.
Rasa cinta pada Indonesia bukan berarti menutup mata atas ketimpangan sosial, kemiskinan yang diwariskan turun-temurun, atau kemunduran demokrasi yang diam-diam dijalankan. Justru karena cinta itulah kita bersuara, menolak tunduk, dan menuntut perubahan. Kita menuntut keadilan sosial bukan demi menggulingkan kekuasaan, melainkan agar kekuasaan kembali kepada fungsi dasarnya: melayani rakyat.
Kita hidup dalam era yang penuh dengan simbol. Nasionalisme dikemas dalam baliho besar dan jargon kosong. Foto pejabat dibingkai bersama bendera, seolah kritik kepada mereka adalah serangan kepada negara. Dalam konteks ini, pernyataan Farid Gaban terasa seperti tamparan bagi kesadaran kolektif: jangan biarkan cinta pada Indonesia dibajak oleh mereka yang kebetulan sedang memegang kuasa.
Jangan biarkan kibaran bendera dijadikan alat untuk membungkam kritik. Jangan biarkan lagu kebangsaan dipakai sebagai pelindung bagi kebijakan yang menindas. Nasionalisme semu seperti ini tak lebih dari kamuflase untuk mempertahankan status quo.
Cinta pada Indonesia tidak boleh buta. Ia harus jernih, rasional, dan bahkan radikal—dalam artian, berani menelusuri akar persoalan. Cinta semacam ini bukan sekadar sentimen. Ia adalah energi yang mendorong kita membela petani yang digusur, buruh yang diabaikan, anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, dan masyarakat adat yang hak-haknya terus dilanggar atas nama investasi dan pembangunan.
Cinta pada Indonesia adalah cinta yang berpihak. Bukan pada penguasa, tetapi pada keadilan. Bukan pada narasi resmi, tetapi pada suara-suara yang selama ini ditekan dan dilupakan. Bukan pada pejabat, tetapi pada nilai-nilai yang memperjuangkan kemanusiaan.
Farid Gaban benar. Dan kita pun harus berani berkata dengan tegas: mencintai Indonesia tidak harus mencintai pemerintahannya, apalagi pejabatnya. Sebab cinta sejati pada negeri ini tidak tunduk pada kekuasaan. Ia tunduk pada cita-cita bersama yang tertulis dalam Pancasila dan UUD 1945—tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentang kedaulatan rakyat.
Pemerintah bisa berganti. Pejabat bisa datang dan pergi. Tapi Indonesia sebagai bangsa, sebagai tanah air, tetaplah milik kita semua. Maka, mari kita cintai Indonesia dengan cara yang paling jujur: menjaga akal sehat, menolak tunduk pada kekuasaan yang menyimpang, dan berdiri di pihak rakyat kecil.
Cinta semacam ini tidak selalu tenang. Kadang marah, kadang kecewa, kadang penuh frustrasi. Tapi cinta seperti inilah yang seharusnya tumbuh dalam diri setiap warga negara. Bukan cinta yang hanya mengangguk dan bertepuk tangan. Tapi cinta yang jujur, kritis, dan berani menyatakan: "Saya cinta Indonesia, tapi saya tidak buta pada kekeliruan pemerintahnya."
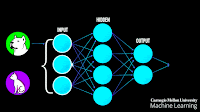
Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit Fenomena buzzer di Indonesia bukan…