Memahami Buzzer sebagai 'Tentara' Digital Bayaran
Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit Fenomena buzzer di Indonesia bukan…
Sinergi Cendekia dan Peduli Kemanusiaan
Dalam percakapan tentang politik kewarganegaraan, Palestina boleh dikata menempati posisi yang unik sekaligus tragis. Jika statelessness berarti manusia tanpa kewarganegaraan, dan invisible citizens berarti warga negara yang tak terlihat atau diabaikan, maka Palestina adalah keduanya sekaligus. Mereka adalah “Denied Citizens”—warga yang secara aktif ditolak, dirampas haknya untuk menjadi bagian sah dari komunitas politik global.
Sejak Nakba 1948, jutaan rakyat Palestina terusir dari tanah kelahiran mereka. Banyak yang kini hidup di kamp-kamp pengungsi di Lebanon, Suriah, atau Yordania dengan dokumen perjalanan sementara, bukan paspor yang diakui. Secara hukum internasional, mereka masuk kategori stateless. Mereka bisa bekerja serabutan, tetapi tidak memiliki hak-hak penuh. Mereka bisa menempuh pendidikan, tapi tak pernah punya kewarganegaraan yang menjamin masa depannya.
Namun bagi yang tetap tinggal di Gaza, Tepi Barat, atau Yerusalem Timur, statusnya bukan lagi stateless, melainkan warga yang tak pernah diakui penuh. Mereka memiliki kartu identitas, tapi bukan kewarganegaraan yang utuh. Di Yerusalem Timur, banyak yang hanya berstatus “residen permanen”—sebuah status yang bisa dicabut kapan saja. Sementara di Gaza, blokade panjang membuat identitas formal mereka nyaris tak berarti: dunia melihat mereka, tetapi tak benar-benar menganggap mereka bagian dari sistem kewarganegaraan global. Sebuah keadaan yang menunjukkan ketidakadilan global.
Inilah yang membuat kasus Palestina berbeda dari kelompok stateless lainnya di dunia. Rohingya di Myanmar misalnya, jelas stateless. Masyarakat adat atau para gelandangan pengemis di berbagai negara bisa disebut invisible citizens. Palestina justru berada di persimpangan atau persilangan keduanya: stateless di pengasingan, invisible di tanah sendiri.
Filsuf Giorgio Agamben pernah menyebut istilah Homo Sacer, manusia yang hidupnya bisa dipertahankan atau dihapuskan kapan saja oleh otoritas tertentu, tanpa perlindungan hukum. Tampaknya Rakyat Palestina berada tepat di situasi itu. Mereka hidup, bekerja, berkeluarga, bahkan berpolitik, tetapi hak-hak fundamental mereka berada dalam “status darurat permanen.” Paling tidak begitu yang terjadi saat ini.
Palestina secara politik memang diakui sebagai negara pengamat non-anggota PBB sejak 2012. Tetapi pengakuan itu tidak otomatis memberi rakyat Palestina paspor yang sah. Banyak negara masih menolak paspor Palestina sebagai dokumen perjalanan resmi. Dengan kata lain, kedaulatan Palestina ada di atas kertas, tapi tidak pernah sepenuhnya turun ke tanah tempat rakyatnya berpijak.
Dalam kacamata demokrasi global, situasi ini adalah paradoks besar. Demokrasi selalu dipuja sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi siapa yang dimaksud “rakyat” ketika jutaan orang diperlakukan seolah tak punya hak untuk memiliki hak? Hannah Arendt pernah menulis, hak paling mendasar manusia adalah “the right to have rights”—hak untuk memiliki hak. Palestina adalah bukti paling nyata bahwa hak itu bisa ditolak, diputarbalikkan, bahkan dihapuskan oleh struktur kekuasaan internasional.
Menjadi “Denied Citizens” berarti hidup dalam ruang hampa kewarganegaraan: diusir dari satu negara, tetapi tidak sepenuhnya diterima negara lain; tinggal di tanah air sendiri, tapi tanpa pengakuan penuh, malah diembargo, diinvasi, dijajah dan beragam tindakan tidak manusiawi lainnya. Sekali lagi mereka bukan hanya stateless, bukan sekadar invisible. Tapi mereka adalah warga yang secara sadar dan sistematis dibonsai oleh politik global.
Pertanyaannya, sampai kapan dunia membiarkan kondisi ini berlangsung? Apakah demokrasi global hanya berlaku untuk mereka yang punya negara kuat, sementara bangsa yang lemah harus puas menjadi catatan kaki sejarah?, dunia, apalagi negara yang mengklaim diri sebagai negara demokratis mesti menjawabnya.
Selama dunia menutup mata, istilah “Denied Citizens” akan terus menjadi identitas tragis rakyat Palestina. Sebuah bangsa yang ada, tapi selalu diingkari keberadaannya.
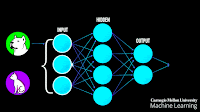
Memahami Fenomena Buzzer dalam 30 Menit Fenomena buzzer di Indonesia bukan…